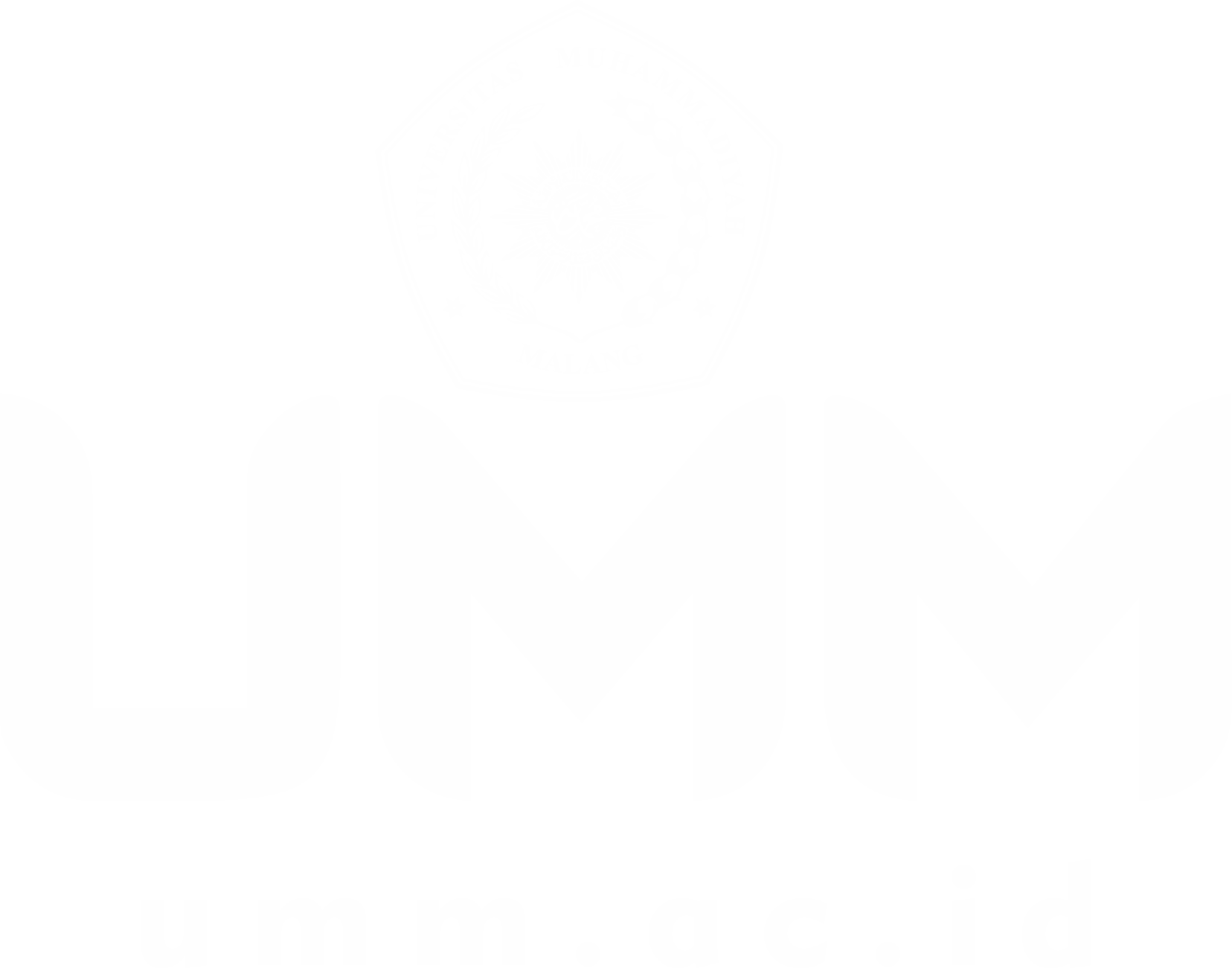KATA ‘teror’, ‘teroris’, dan ‘terorisme’ semakin terbiasa terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Salah satu yang memopulerkan kata-kata tersebut ialah media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring (online) yang secara serentak memberitakan peristiwa yang terkait dengan aksi teror. Bahkan, karena kekuatan makna di balik kata teror itu pula, Media Indonesia (MI) menurunkan headline berita pada edisi Selasa, 14 Maret 2017, dengan judul ‘Aktor Teror Spanduk Diusut’.
Tak hanya itu, pada editorialnya, MI juga memilih judul ‘Memberangus Teroris Politik’ (hlm 2) dan editorial 13 Maret 2017 di rubrik Suara Anda (hlm 9) dengan judul ‘Teror Politik’.
Pemaknaan teror tersebut dikonstruksikan untuk menyebut orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik. Makna teror dalam konteks politik ini menarik untuk dikaji secara kritis karena beberapa hal.
Pertama, makna teror selama ini adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi dan bersifat transnasional. Nur Ali (dalam Khairil, 2011) membedakan makna tersebut. Terorisme merupakan suatu mazhab/aliran atau kepercayaan melalui pelaksanaan kehendak guna menyuarakan pesan dan atau asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjurus ke arah kekerasan, kebrutalan, dan bahkan pembunuhan.
Teroris berarti pelaku atau pelaksanaan bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan, ataupun kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan, disertai pengunaan berbagai senjata mulai yang konvensional sampai senjata modern. Teror ialah bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan cara ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, perusakan atau penghancuran, penculikan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan.
Alat teror ialah sarana yang digunakan dalam aksi teror yang dapat berupa selebaran, telepon, bom, dan berbagai senjata yang dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan.
Tujuan terorisme untuk melumpuhkan otoritas pemerintah sehingga dapat menerapkan mazhab dan/atau aliran yang dianut kelompok terorisme.
Berdasarkan makna tersebut, teror politik dan teroris politik pada perkembangannya dapat pula menjadi terorisme politik jika perilaku kekerasan dilakukan di ranah politik.
Tentu saja, terorisme politik ini tidak boleh dibatasi hanya pada pertarungan pilkada, tetapi bisa ditarik dalam ranah pertempuran politik yang tidak lagi menggunakan etika politik dan akal sehat, seperti politik pembunuhan karakter, politik uang, politik dagang sapi, politik suap, politik kambing hitam, dan politik pelenyapan suara, dan politik ‘keras’ sejenis.
Dalam konteks komunikasi politik sudah banyak terjadi terorisme politik berupa penggunaan kekerasan dalam menghadapi lawan-lawan politik. Penyebarluasan kebencian, konstruksi permusuhan, dan nalar politik adu domba merupakan teror politik yang harus diwasapadai hingga hari ini.
Kedua, ditarik makna yang lebih luas, terorisme politik dapat pula ditampakkan dari tindakan politik politisi yang berani bertindak ‘keras’ menguras uang rakyat (korupsi), menipu harapan berjuta-juta rakyat setelah menjadi penguasa, menggembosi dana bantuan sosial (bansos) yang semestinya untuk rakyat.
Memanipulasi jumlah warga miskin, mengeksploitasi masyarakat lemah demi keberhasilan politiknya, hingga politisasi agama demi tujuan pragmatis politik. Terorisme politik seperti ini tak ubahnya aksi para teroris yang meledakkan sarana umum, melukai masyarakat tak berdosa. Bedanya hanya dalam konteks kepentingan yang ingin diraih, tetapi cara-caranya tidak jauh beda.
Jika aksi teroris yang menggunakan simbol agama melakukan kekerasan berkepentingan untuk menarik simpati kelompok luar agar memahami ideologi dan ‘mau’ mengikuti, terorisme politik dapat melakukan politik pencitraan dengan cara mengambinghitamkan lawan politiknya dengan harapan dapat meraih dukungan rakyat melalui agitasi publik.
Jika ‘sang teroris’ membunuh warga yang tidak berdosa, terorisme politik dapat membunuh karakter lawan politiknya dan ‘membunuh’ harapan rakyat yang dijanjikan saat kampanye yang kemudian diingkarinya. Jika ‘para teroris’ merusak fasilitas umum sebagai simbol perlawanan kepada aparat, terorisme politik dapat berulang kali merusak fasilitas negara melalui politik ‘bancakan anggaran’ proyek yang disunatnya.
Demikian juga, aksi teroris sengaja dilakukan agar mendapatkan perhatian media massa dan dapat menyampaikan pesan ideologi yang memprotes ketidakadilan, kemiskinan, dominasi, dan kesenjangan yang terjadi.
Namun, bagi teroris politik, mereka dapat membangun citra diri melalui debat tentang pemberdayaan masyarakat, pemberantasan pungli, penegakan hukum.
Namun, para teroris politik ini diam-diam mengamankan kasus yang sedang membelitnya. Maka, sering kali kita dapati, teroris politik ini berkoar-koar tidak bersalah di depan awak media massa, tetapi tidak berdaya setelah vonis hukum menjeratnya.
Fenomena terorisme politik ini hampir mirip yang terjadi di ruang ekonomi di saat terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ekonomi yang digunakan hanya kepentingan golongan tertentu sehingga melahirkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi sebagai bentuk terorisme ekonomi.
Melawan arus terorisme politik
Terorisme politik akan sulit dihilangkan apabila tidak ada teladan dari para elite politisi dalam menampilkan etika politik yang bermartabat tidak dilakukan. Pertama, memperbaiki komunikasi politik sebagai bentuk revolusi mental politik.
Para elite sudah semestinya berpikir dan bertindak untuk kepentingan rakyat, mendidik masyarakat menjadi kritis dan konstruktif terhadap kebijakan, dan terus berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya. Membangun moralitas politik secara terus-menerus harus dilakukan agar semakin banyak kekuatan yang mengedepankan rakyat yang telah memberikan amanah politik kepada mereka.
Kedua, jika yang pertama tidak dilakukan, rakyat sendiri yang akan melakukan perlawanan kepada para teroris politik tersebut. Hal itu penting dicatat bahwa rakyat sendiri dibuat ‘melek’ terhadap perilaku terorisme politik itu justru dari tindakan politik para elite dan penguasa tersebut. Sudah jelas, mereka dibayar dari jerih payah keringat rakyat, para teroris ini justru ‘memain-mainkan’ kepentingan rakyat.
Logika hati nurani rakyat akan ‘jujur bersuara’ bahwa mereka harus melawan dengan caranya sendiri: mulai diam (diam dalam pandangan kritis termasuk bentuk perlawanan), bersuara lantang, hingga menghukum moral dengan cara rakyat. Suatu ketika rakyat dapat mengatakan, “Terorisme politik sama jahatnya dengan terorisme yang lain,” dan “jangan disalahkan” rakyat memaknai realitas tersebut.
Akhirnya, mencermati dinamika politik yang terus berkembang, tidak ada kata yang terlambat untuk menghentikan laju gerak para teroris politik yang telah menyebarkan ajaran ‘terorisme politik’ di Tanah Air.
Semua elemen bangsa ini, yang masih bersuara dengan kebenaran, akan dapat menghadang teror politik dengan moralitas politik yang sesuai dengan fitrah manusia, akal sehat, dan yang menenteramkan jiwanya.